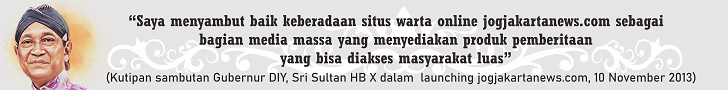“Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, serta abolisi kepada mantan Menteri Tom Lembong menandai perubahan penting dalam arah kebijakan hukum – politik Indonesia pascareformasi.”
Secara formal, langkah ini dikemukakan sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi dan penguatan demokrasi.
Namun jika ditelaah secara lebih mendalam, kebijakan tersebut memperlihatkan bagaimana bahasa kekuasaan digunakan secara strategis untuk membingkai, membentuk, bahkan mengaburkan makna hukum dan moralitas di mata publik.
Dalam perspektif linguistik wacana, istilah “amnesti” dan “abolisi” bukan sekadar kategori yuridis, melainkan penanda ideologis yang membawa beban historis dan etis tertentu.
Dalam konteks klasik, amnesti diberikan dalam situasi pascakonflik yang melibatkan pelanggaran politik, sedangkan abolisi biasanya diterapkan dalam kerangka restoratif untuk kepentingan kemanusiaan atau transisi keadilan.
Namun dalam narasi resmi pemerintahan saat ini, kedua istilah tersebut mengalami pergeseran semantik: ia dijauhkan dari bobot moral-historisnya dan direduksi menjadi simbol teknokratis kebijakan “pemulihan kepercayaan” dan “pengembalian aset negara.”
Pergeseran makna ini tampak jelas dalam pernyataan Presiden yang menyebut:
“Kita memberikan pengampunan bukan karena kelemahan hukum, tetapi karena semangat menyatukan bangsa yang sempat terbelah.”
Ucapan ini secara retoris mengaburkan batas antara kebijakan politik dan prinsip hukum. Istilah “menyatukan bangsa” adalah metafora integratif yang secara emosional positif, tetapi dalam konteks ini digunakan untuk menutupi penghilangan akuntabilitas hukum.
Presiden tidak merinci proses hukum yang sedang berlangsung, melainkan menggantinya dengan bahasa moral yang membingkai pengampunan sebagai tindakan kenegarawanan.
Pakar hukum Universitas Indonesia, Heru, menyebut kebijakan ini sebagai “drama politik,” bukan peristiwa hukum yang otonom.
Ia menyoroti bahwa kasus Hasto maupun Lembong belum sampai pada fase inkrah yang secara lazim menjadi syarat pemberian pengampunan negara.
Dengan demikian, keputusan ini menunjukkan adanya pelompatan prosedural yang dibingkai secara simbolik sebagai tindakan heroik. Kata-kata seperti “rekonsiliasi” dan “kemanusiaan” berfungsi bukan untuk menjelaskan, melainkan menormalisasi keputusan yang bermuatan politis.
Bahasa dalam hal ini tidak lagi menjadi sarana deskripsi realitas, melainkan alat legitimasi kekuasaan.
Seperti ditegaskan oleh Norman Fairclough dalam kerangka Critical Discourse Analysis, ketika kekuasaan menggunakan bahasa untuk membingkai realitas tertentu sebagai “normal”, “rasional”, atau bahkan “manusiawi”, maka sesungguhnya sedang terjadi proses naturalization of ideology.
Pilihan diksi seperti “pemulihan aset” atau “rekonsiliasi nasional” menyamarkan dimensi impunitas yang terkandung dalam pengampunan tersebut.
Di sini, bahasa tidak sekadar menyampaikan, tetapi menciptakan kebenaran versi negara.
Praktisi hukum Agus Widjajanto mempertanyakan motif di balik kebijakan tersebut: apakah benar-benar didasarkan pada rasa keadilan masyarakat atau justru kalkulasi politik kekuasaan? Ia menekankan bahwa pengampunan terhadap pelaku korupsi yang dikaitkan dengan pengembalian aset negara menciptakan preseden bahwa kejahatan dapat ditebus secara ekonomis, bukan secara etik dan pidana.
Dalam pandangan ini, keadilan tidak lagi bersandar pada pertanggungjawaban hukum, melainkan pada kemampuan negosiasi. Frasa Presiden:
“Kita tidak ingin terjebak dalam dendam masa lalu, mari kita fokus pada pemulihan.”
terdengar meneduhkan, namun secara wacana adalah bentuk delegitimasi terhadap kebutuhan akan keadilan hukum. Kata “dendam” di sini bukan hanya membingkai pengadilan sebagai sesuatu yang tidak produktif, tetapi juga mengasosiasikan tuntutan keadilan sebagai tindakan balas dendam, bukan sebagai proses keadilan restoratif.
Di sinilah bahasa bertemu dengan struktur sosial.
Dalam perspektif sosiologis, pernyataan dan narasi yang digunakan dalam pidato-pidato kekuasaan ini mencerminkan bagaimana negara mendefinisikan ulang makna keadilan secara vertikal, tanpa deliberasi (pembahasan bersama) dengan masyarakat. Pierre Bourdieu menyebut ini sebagai symbolic violence—kekerasan simbolik yang dilakukan oleh mereka yang memiliki otoritas untuk mendefinisikan realitas sosial.
Bahasa bukan hanya alat komunikasi, melainkan mekanisme kuasa untuk mengatur siapa yang berhak berbicara, apa yang layak diucapkan, dan makna mana yang dianggap sah.
Azmi Syahputra, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, menyatakan bahwa meski keputusan presiden sah sebagai hak prerogatif, tetap merupakan kebijakan politik yang sarat makna.
Frasa-frasa seperti “langkah berani”, “terobosan kebijakan”, atau “penyatuan kembali bangsa” adalah bagian dari strategi hegemonik yang menyamakan tindakan politis dengan moralitas nasional.
Secara linguistik, ini adalah bentuk dari hegemonic discourse yang menyamarkan konflik nilai melalui pengulangan narasi yang terdengar konvergen dan solutif.
Namun dari sudut sosiologi wacana, kita melihat bahwa dampak dari retorika ini lebih dari sekadar permainan kata.
Ia berdampak pada struktur persepsi publik.
Masyarakat menjadi penonton dalam drama rekonsiliasi elite, tanpa akses terhadap proses deliberatif (musyawarah terbuka) yang adil dan transparan.
Dalam istilah Jurgen Habermas, ini adalah bentuk distorsi komunikasi publik, di mana rasionalitas hukum digantikan oleh narasi emosional yang tak bisa diuji secara kritis.
Media pun tampak ikut melestarikan konstruksi wacana ini.
Dalam banyak pemberitaan, porsi analisis kritis sangat terbatas. Frasa-frasa seperti “kontroversial”, “impunitas”, atau “pengabaian prinsip due process” nyaris tidak terdengar.
Alih-alih menjadi ruang deliberasi publik yang kritis, media justru lebih sering memperkuat narasi kekuasaan. Akibatnya, ruang publik berubah menjadi ruang resonansi, bukan lagi ruang kontestasi.
Wacana tandingan tersingkir karena tak punya dukungan infrastruktur simbolik yang cukup kuat.
Di sinilah kita menyaksikan bagaimana legitimasi hukum dibentuk bukan oleh prosedur, tetapi oleh performa bahasa.
Lebih jauh, rekayasa makna melalui bahasa kekuasaan semacam ini berpotensi membentuk budaya hukum yang permisif terhadap elite, sekaligus membangun apa yang oleh para sosiolog disebut sebagai fatalisme politik masyarakat.
Ketika publik terbiasa menyaksikan penyimpangan prosedural dibungkus dengan narasi moral dan nasionalisme kosong, maka lambat laun akan tumbuh sikap apatis, sinis, dan bahkan skeptis terhadap institusi negara.
Keadilan tak lagi diyakini sebagai sesuatu yang dapat diperjuangkan melalui hukum, melainkan sebagai hasil dari kedekatan politik dan transaksi kekuasaan.
Dalam jangka panjang, kondisi ini melemahkan partisipasi warga dalam demokrasi, mengaburkan batas antara legalitas dan kepentingan, serta menormalisasi penyimpangan dengan dalih stabilitas.
Dengan kata lain, yang tergadaikan bukan hanya kepercayaan hukum, tetapi juga kesadaran kritis masyarakat sebagai warga negara.
Rekonsiliasi tentu bukan hal yang perlu ditolak dalam kehidupan berbangsa. Namun rekonsiliasi yang sejati hanya dapat dibangun di atas landasan transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum. Ketika pengampunan diberikan tanpa proses hukum yang terbuka dan ketika bahasa digunakan untuk menutupi motif politik, maka rekonsiliasi berubah menjadi retorika kosong yang menjauhkan publik dari substansi keadilan.
Bahasa, dalam konteks ini, tidak netral. Ia adalah medan kuasa, instrumen legitimasi, dan sarana reproduksi ideologi.
Amnesti dan abolisi bukan hanya kebijakan administratif, tetapi praktik simbolik yang memperlihatkan bagaimana kekuasaan mengatur ingatan, mengatur makna, dan mengatur persepsi publik.
Ketika bahasa negara tidak lagi berpihak pada kebenaran substantif, kita tidak hanya menyaksikan pelemahan hukum, tetapi juga kemunduran demokrasi yang berjalan diam-diam—bukan dengan represi senjata, tetapi dengan rekayasa kata-kata dan penjinakan makna.
*Penulis adalah Alumni PP. Lirboyo Kediri, Dosen Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta