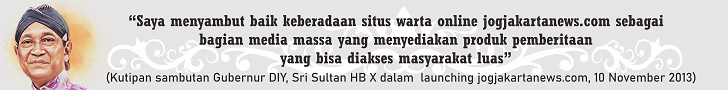“Dalam ruang hukum yang semakin kompleks, vonis terhadap Thomas Trikasih Lembong ( Tom Lembong ) menandai sebuah momen penting dalam sejarah relasi antara kebijakan publik dan tindak pidana korupsi.”
Mantan Menteri Perdagangan itu dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara atas penerbitan izin impor gula kristal mentah yang disebut telah merugikan keuangan negara.
Putusan ini bukan semata perkara administratif atau prosedural, melainkan menyingkap sesuatu yang lebih mendasar: pergeseran makna korupsi dari persoalan niat jahat menjadi persoalan akibat kebijakan.
Dalam pergeseran inilah, tampak bahwa bahasa hukum tidak lagi netral—ia menjadi instrumen kekuasaan yang menentukan mana yang disebut kejahatan, meskipun tidak ada pelaku yang memperkaya diri.
Majelis hakim menyatakan bahwa meskipun tidak ditemukan niat jahat dan tidak ada keuntungan pribadi yang diperoleh oleh Lembong, tindakannya telah menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar, dan itu sudah cukup untuk memenuhi unsur pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Logika hukum yang dipakai adalah logika akibat: dampak finansial dianggap lebih penting daripada motif kebijakan. Hukum dalam konteks ini bekerja sebagai sistem formalisme tekstual—di mana penyimpangan dari prosedur administratif, jika berdampak secara fiskal, secara otomatis diklasifikasikan sebagai korupsi.
Tidak ada ruang untuk mempertimbangkan kompleksitas pengambilan keputusan dalam pemerintahan, yang sering kali harus bersandar pada proyeksi dan pertimbangan darurat.
Sebaliknya, pembelaan terhadap Tom Lembong menekankan pentingnya membedakan antara kesalahan administratif dengan niat kriminal.
Melalui nota pembelaan yang tajam dan reflektif, Lembong membingkai kasusnya sebagai kriminalisasi atas kebijakan publik yang dijalankan dengan itikad baik dalam konteks kestabilan harga pangan nasional.
Ia tidak menyangkal bahwa keputusan yang diambil berdampak besar, tetapi mempertanyakan keadilan jika seorang pejabat dijatuhi hukuman penjara tanpa bukti adanya niat menyimpang maupun keuntungan pribadi.
Strategi pembelaan ini bekerja tidak hanya secara hukum, melainkan juga secara wacana: ia menantang konstruksi bahasa hukum yang memisahkan tindakan dari konteks, dan menyoroti absurditas ketika kejujuran justru dijatuhi hukuman.
Dalam narasi jaksa, tindakan Lembong diposisikan sebagai pelanggaran prosedur yang menyebabkan kerugian fiskal. Bahasa yang digunakan mengedepankan diksi legal dan teknokratis: “tidak sesuai rekomendasi,” “mengabaikan peran BUMN,” dan “menguntungkan pihak swasta.”
Bahasa ini membangun asosiasi langsung antara keputusan administratif dan dampak negatif terhadap negara, seolah tidak ada alternatif pembacaan atas kompleksitas kebijakan perdagangan internasional dan intervensi pasar.
Melalui repetisi istilah kerugian negara, jaksa mengukuhkan persepsi bahwa nilai rupiah yang hilang—terlepas dari bagaimana dan mengapa—adalah bukti mutlak tindak pidana.
Namun dalam ruang publik, narasi ini tidak diterima begitu saja.
Perdebatan di media sosial, ruang akademik, dan forum digital menunjukkan resistensi yang luas terhadap penggunaan hukum untuk menghukum kegagalan kebijakan.
Banyak pihak mempertanyakan validitas pasal-pasal dalam UU Tipikor yang memungkinkan pejabat negara dipidana tanpa perlu pembuktian niat jahat, cukup dengan membuktikan kerugian negara secara material.
Kritik ini merefleksikan ketegangan antara dua paradigma besar: paradigma hukum sebagai penjaga prosedur, dan paradigma hukum sebagai instrumen keadilan substantif.
Jika hukum diberlakukan secara kaku terhadap pejabat yang mengambil keputusan dalam kondisi dinamis, maka bukan hanya integritas birokrasi yang terancam, tetapi juga keberanian untuk berinovasi. Dalam kerangka ini, vonis terhadap Lembong menciptakan preseden yang berbahaya: bahwa seorang menteri dapat dipenjara karena mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan, meskipun tidak ada niat menyimpang.
Bahasa hukum telah menyempitkan ruang kebijakan, dan dalam penyempitan itu pula, hukum kehilangan kepekaannya terhadap kenyataan politik, ekonomi, dan moral yang menyertai pengambilan keputusan publik.
Oleh karena itu, kasus ini harus dibaca tidak hanya sebagai peristiwa hukum, tetapi sebagai peristiwa diskursif: saat di mana makna korupsi diredefinisi oleh kekuatan yang bekerja melalui bahasa.
Kita menyaksikan bagaimana suatu tindakan administratif dimaknai sebagai tindak pidana bukan karena adanya niat jahat, tetapi karena bahasa hukum memungkinkan perluasan makna korupsi hingga menyentuh ranah kebijakan. Maka, pertanyaan mendasarnya bukan lagi apakah Tom Lembong bersalah secara hukum, tetapi apakah bahasa hukum kita masih mampu membedakan antara kegagalan kebijakan dan kejahatan yang sesungguhnya.
Kasus ini menunjukkan bahwa hukum bukan sekadar kumpulan norma, melainkan medan pertarungan makna. Siapa yang memegang kendali atas definisi “korupsi” akan menentukan siapa yang akan dilindungi, dan siapa yang akan dihukum. Dalam konteks ini, redefinisi korupsi bukan hanya konsekuensi dari perkembangan hukum, tetapi juga dari krisis keadilan itu sendiri.(*)
*Penulis adalah Alumni PP. Lirboyo Kediri, Dosen Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta