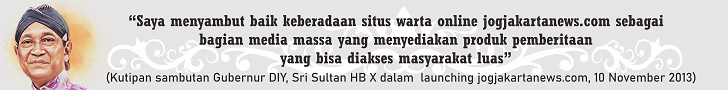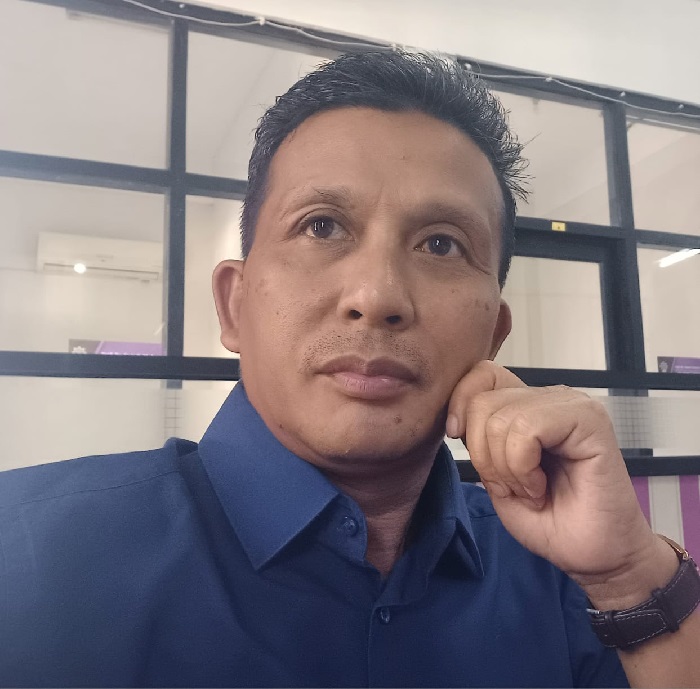Fenomena thrifting menjadi lifestyle bagi anak muda Indonesia. Di pasar daring, toko maupun lapak jalanan, pakaian impor bekas dari Korea, Jepang, dan Eropa laris manis diburu konsumen yang ingin tampil modis dengan harga murah. Kata thrift dalam bahasa Inggris secara harfiah berarti penghematan. Akar katanya berasal dari bahasa Inggris Kuno þrift, berarti prosperity atau well-being, artinya kemakmuran yang diperoleh karena hidup sederhana dan efisien. Dalam budaya populer, maknanya bergeser menjadi aktivitas membeli barang bekas yang masih layak pakai.
Thrifting mencerminkan ketimpangan ekonomi struktural. Di sisi lain, menggambarkan manifestasi gaya hidup baru kelas menengah muda yang ingin tampil sadar lingkungan dengan hemat, tetapi tetap modis. Di balik itu semua, ternyata menyimpan persoalan ekonomi yang tidak sederhana. Pemerintah melalui Permendag No. 40 Tahun 2022 telah melarang impor pakaian bekas karena dianggap membahayakan kesehatan, merusak industri tekstil, dan membuka peluang penyelundupan. Ironisnya, meskipun telah ada larangan tersebut, pasar thrift justru tumbuh pesat, memanfaatkan celah ekonomi digital dan lemahnya pengawasan di pelabuhan.
Kalau dulu thrifting identik dengan lapak kaki lima atau pasar loak di Tanah Abang, Pasar Senen, atau Gedebage Bandung. Saat ini ekosistemnya sudah berubah drastis. Banyak penjual membuka toko online thrift di Instagram, TikTok Shop, Shopee, dan marketplace lainnya. Mereka memanfaatkan algoritma media sosial untuk menjual pakaian bekas dengan gaya promosi yang kreatif seperti flat lay aesthetic, haul video, atau live streaming sale dengan narasi vintage dan sustainable fashion.
Dari sisi fiskal, negara berpotensi kehilangan penerimaan pajak dan bea masuk dalam jumlah besar. Barang-barang thrift yang masuk lewat jalur tidak resmi tentu tidak tercatat dalam sistem kepabeanan. Akibatnya, negara tidak memperoleh bea impor, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penghasilan (PPh) dari pelaku usaha yang bergerak di sektor ini. Jika dibiarkan, praktik ini bisa menjadi shadow economy yang menggerogoti fondasi keuangan negara. Ibarat kebocoran kecil, lama-lama melubangi kapal besar bernama ekonomi nasional.
Dampak lain yang tak kalah serius adalah tergerusnya daya saing industri tekstil dalam negeri. Produk thrift yang dijual sangat murah sulit disaingi oleh produsen lokal. Padahal, industri tekstil dan garmen merupakan salah satu penyumbang lapangan kerja terbesar di Indonesia. Ketika pasar domestik dibanjiri produk bekas impor, pabrik-pabrik bisa kehilangan permintaan. Akibatnya memicu pengurangan tenaga kerja, dan akhirnya mengurangi kontribusi pajak ke negara. Setiap pakaian bekas yang dibeli konsumen bisa berarti hilangnya peluang kerja bagi saudara sebangsa.
Menyadari dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan, pemerintah berencana menegakkan kembali aturan impor pakaian bekas untuk melindungi industri sandang dalam negeri sekaligus menj aga kesehatan publik. Langkah ini merupakan upaya afirmatif untuk menegakkan kedaulatan ekonomi nasional. Namun pada saat yang sama, diperlukan kebijakan transisi yang adil. Negara perlu memastikan agar pelaku usaha kecil yang menggantungkan hidup pada perdagangan pakaian bekas tidak tersingkir, melainkan diarahkan menuju sektor produksi baru yang lebih berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan nasional.
Kedaulatan sandang bukan sekadar kemampuan menutup tubuh, tetapi kemandirian dalam memproduksi dan memaknai pakaian sebagai simbol budaya dan harga diri bangsa. Ketika pasar domestik dibanjiri pakaian bekas impor, bukan hanya industri konveksi dan UMKM yang terpukul, melainkan juga semangat berdikari yang diwariskan para pendiri bangsa. Dalam konteks ini, sepertinya pemerintah harus hadir menjaga kadeaulatan sandang.
Dalam perspektif ekonomi Islam, kemandirian produksi dan pengelolaan sumber daya lokal merupakan bagian dari prinsip istiqlal al-iqtisadiyah (kemandirian ekonomi) yang akan menopang kehormatan rakyat (‘izzah ar-ra’iyyah). Konsumsi tidak diukur semata oleh harga murah, tetapi oleh nilai manfaat dan keberkahan. Tren thrifting yang digerakkan oleh keinginan tampil gaya dengan biaya rendah sering kali terjebak pada logika israf (pemborosan). Membeli bukan atas dasar kebutuhan, melainkan dorongan tren dan citra diri. Islam menuntun agar konsumsi diarahkan pada maslahah dan keberlanjutan, bukan pada gaya hidup imitasi yang dampaknya memperlemah daya saing produksi lokal.
Dalam konteks inilah, semangat lama Aku Cinta Produk Indonesia (ACI) yang pernah digaungkan pada dekade 1980-an layak dihidupkan kembali. Tentunya bukan sekadar slogan, melainkan ajakan moral untuk mencintai, membeli, dan memakai hasil karya bangsa sendiri. Gerakan cinta produk lokal adalah wujud nyata hubb al-wathan (cinta tanah air) yang berpadu dengan kesadaran spiritual.
Menarik apa yang pernah dikatakan Mahatma Gandhi, it is better to be poor and self-sufficient than rich and dependent (Lebih baik miskin namun mandiri, daripada kaya tetapi bergantung). Gagasan ini sejalan dengan semangat Swadesinya, yaitu gerakan cinta produksi dalam negeri. Berupaya mengurangi ketergantungan berlebihan pada barang impor dan menumbuhkan kedaulatan ekonomi rakyat. Pakaian seharusnya dipahami bukan sekadar urusan mode, tetapi juga sebuah moralitas dan martabat bangsa. (*)
*Penulis adalah Dosen UIN Salatiga dan Guru Besar Ekonomi Islam, Pengampu Ekonomi Islam Internasional